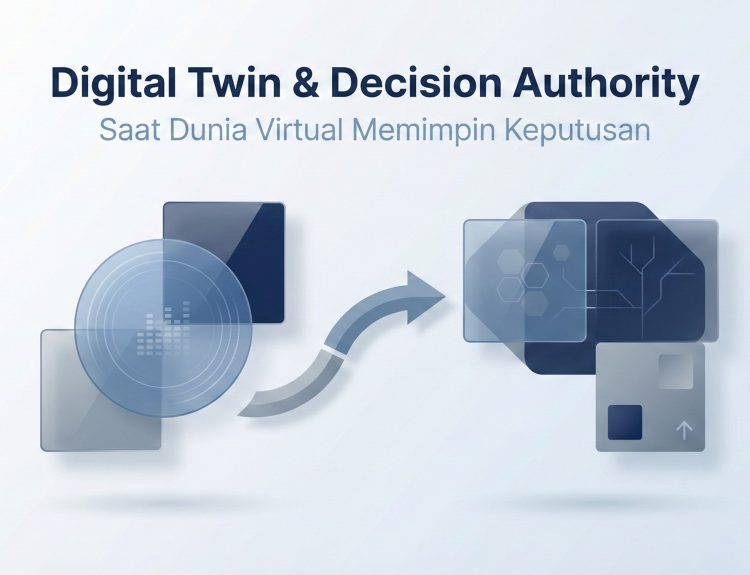Arriving Softly – Datang Tanpa Dikejar Waktu
Kami tiba di Yogyakarta sekitar pukul empat sore. Saya, istri, dan anak-anak memasuki kota ini ketika cahaya masih utuh dan gerimis turun pelan, nyaris seperti bisikan. Hujan itu tidak memaksa siapa pun berlari; ia hanya menurunkan tempo, seolah kota ini ingin kami datang tanpa tergesa.
Di beberapa simpang, kendaraan bergerak perlahan. Ada kepadatan, tetapi tidak agresif. Klakson terdengar seperlunya. Petugas lalu lintas memberi isyarat dengan gerakan tenang. Warga lokal bergerak seolah sudah hafal irama kota wisata—ramai, iya, tapi tidak perlu tergesa. Yogyakarta tidak menuntut kami cepat sampai; ia memberi waktu untuk benar-benar tiba.
Anak-anak di kursi belakang memandangi jalanan basah dan pejalan kaki yang tetap santai. Tidak ada keluhan. Kepadatan sore itu terasa seperti jeda—ruang kecil untuk menarik napas sebelum masuk ke ritme kota.

Sekitar satu jam kemudian, kami tiba di hotel. Gerimis belum sepenuhnya berhenti. Kami memilih berhenti. Anak-anak beristirahat, istri membuka jendela sedikit agar udara Yogya masuk pelan-pelan. Malam pertama kami lewati dengan obrolan ringan: pekerjaan, arah karier, dinamika kantor, teman-teman lama, dan hal-hal yang sedang diminati. Tanpa agenda. Tanpa target wisata. Hanya hadir.
Hari pertama berakhir seperti kalimat pembuka yang tenang—cukup untuk membuat siapa pun ingin melanjutkan cerita.
When Time Slows Down – Saat Waktu Duduk Bersama

Hujan masih turun keesokan harinya. Setelah sarapan, kami tidak ke mana-mana. Hotel menjadi ruang tunggu yang nyaman. Menjelang siang, kami mengunjungi keluarga yang tinggal tak jauh dari sini. Hari kedua mengalir tanpa jadwal dan tanpa ambisi.
Obrolan siang dan sore berjalan alami. Siang hari diisi cerita keseharian—pekerjaan, perubahan ritme kerja, dinamika karier yang tak lagi lurus. Menjelang sore, percakapan berubah menjadi refleksi: tentang prioritas yang bergeser, tentang peran teman-teman lama, tentang bagaimana hidup perlahan mengajarkan memilih yang cukup.
Anak-anak ikut bercerita tentang minat mereka—teknologi, olahraga, musik, rencana-rencana kecil yang membuat mata mereka berbinar. Saya menyeruput kopi rasa durian untuk pertama kalinya. Awalnya ragu, lalu hangat. Singkong goreng dan keripik menemani. Angin sore membawa sisa hujan, membuat waktu terasa enggan bergerak cepat.
Di momen itu, ingatan saya melayang ke sore-sore di Madrid dan lorong pejalan kaki di Barcelona—kota-kota yang membiarkan orang duduk lama tanpa agenda. Pengalaman seperti ini selaras dengan pandangan Greg Richards, seorang akademisi dan konsultan pariwisata budaya yang puluhan tahun mendampingi kota-kota wisata dunia. Richards dikenal karena menekankan bahwa daya tarik kota justru lahir dari aktivitas harian warganya—berjalan, mengobrol, menunggu—bukan dari atraksi besar yang dipaksakan.
Hari itu berlalu tanpa foto ikonik. Namun kami tidur dengan rasa cukup.
Walk the City – Kota yang Mengajak Kita Melangkah

Hari berikutnya, langit cerah sejak pagi. Pukul lima-an, sekitar jam 05.00 lewat, saya berjalan berdua dengan istri. Anak-anak masih terlelap. Udara segar dan ringan, seperti undangan untuk melangkah tanpa rencana.
Kami berjalan menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta, melewati Pasar Beringharjo yang mulai bangun. Di dekat kantor gubernur, kami melihat antrean pengunjung mengenakan pakaian adat. Ada yang dirias, ada yang menunggu giliran difoto. Mereka tertawa, saling menyapa, menikmati prosesnya.

Pemandangan itu terasa penting. Kota ini tidak hanya memamerkan budaya; ia memberi ruang bagi pengunjung untuk ikut masuk dan mencoba—tanpa canggung.
Tepat pukul enam, kami tiba di Titik Nol. Musik terdengar. Pemanasan dimulai. Senam pagi berlangsung tanpa sekat. Warga lokal dan pengunjung bergerak bersama. Gerakannya tidak selalu rapi, tetapi tawa mengisi udara.
Saya teringat pagi-pagi di Milan, Zurich, dan Wina—kota-kota yang hidup karena ruang publiknya digunakan bersama. Di sinilah pemikiran Jan Gehl terasa nyata. Gehl adalah arsitek dan konsultan kota asal Denmark yang dikenal luas sebagai pelopor konsep human-scale city. Ia percaya kota yang baik adalah kota yang nyaman untuk berjalan kaki dan memberi ruang bagi perjumpaan kecil. Yogya melakukannya tanpa jargon dan tanpa pamer konsep.
Usai senam, kami menyusuri Malioboro. Toko-toko berdiri berdekatan, sederhana, jauh dari kemegahan mal. Berjalan kaki menjadi cara utama menikmati kota. Kami mampir ke toko batik favorit, lalu kembali ke hotel dengan becak mesin—ritme kota terasa konsisten sejak pagi.
Breakfast & Patience – Sarapan, Menunggu, dan Rasa Diterima
Menjelang pukul delapan, restoran hotel sudah ramai. Ada keluarga dengan mobil pribadi, rombongan dari bus besar dan bus kecil, pasangan muda dengan ransel, serta wisatawan yang akrab dengan transportasi umum. Semua bercampur tanpa jarak.

Pelayanan pagi itu berjalan biasa saja. Ada janji meja yang perlu waktu lebih lama. Ada tamu yang langsung duduk di meja kosong meski antrean masih ada. Saya dan istri saling pandang, lalu tersenyum. Anehnya, tidak ada rasa kesal—semua terasa ringan.
Mungkin karena pagi tadi sudah begitu hangat. Seperti yang sering disampaikan Anna Pollock, seorang pemikir dan konsultan pariwisata yang dikenal lewat gerakan Conscious Travel. Pollock banyak menekankan bahwa suasana emosional sebuah destinasi menentukan perilaku wisatawan. Ketika kota terasa ramah dan manusiawi, ketidaksempurnaan layanan justru lebih mudah diterima.
Sambil menikmati sarapan, kesimpulan itu terasa jelas: Yogyakarta ramah bagi siapa pun. Datang bersama keluarga dengan mobil sendiri, datang berombongan dengan bus, datang berdua naik transportasi umum—semuanya bisa menikmati kota ini dengan caranya masing-masing. Tidak ada satu cara yang dianggap paling benar.

Pemikiran John Urry terasa hidup di sini. Urry adalah sosiolog Inggris yang memperkenalkan konsep the tourist gaze—cara wisatawan memandang dan mengalami sebuah tempat. Ia percaya wisata bukan soal apa yang dilihat, melainkan bagaimana seseorang merasakan keseharian kota tersebut. Pandangan ini dilengkapi oleh Erik Cohen, antropolog pariwisata yang menekankan bahwa destinasi paling dikangeni adalah yang membuat pengunjung merasa diterima sebagai manusia, bukan sekadar konsumen.
Yogyakarta mungkin belum sempurna dalam setiap detail layanan. Namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting: rasa diterima. Itulah yang membuat orang datang, pulang, lalu ingin kembali.
Sarapan pagi itu menutup perjalanan kami. Sederhana. Sedikit menunggu. Banyak tersenyum.
Dan pelan-pelan, kami pulang—membawa makna.
Referensi
- John Urry, The Tourist Gaze, Sage Publications, 1990
- Erik Cohen, Contemporary Tourism: Diversity and Change, Elsevier, 2004
- Greg Richards, Rethinking Cultural Tourism, Edward Elgar Publishing, 2018
- Anna Pollock, The Future of Conscious Travel, Conscious Travel Reports, 2023–2024